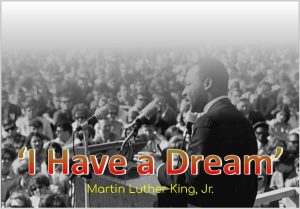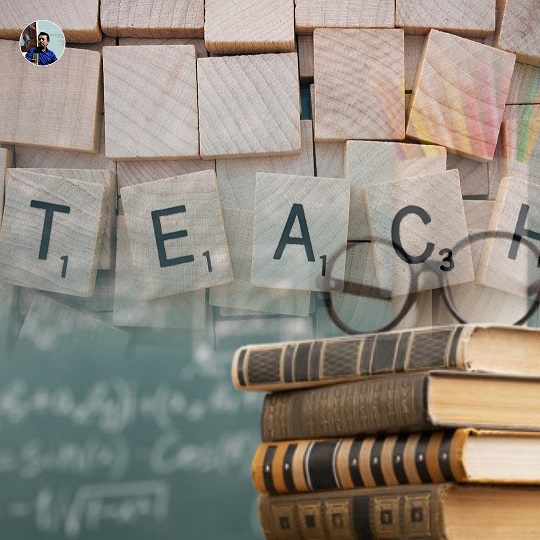Haruskah Dinasti Kekuasaan Ada Lagi?

Saat ini perbicangan mengenai bakal cawapres di antara capres cukup hangat. Uji materi UU Pemilu terkait syarat usia capres-cawapres yang akan dibacakan besok pada Senin 16 Oktober 2023.
Ketika opini ini ditulis, penulis berpikir bahwa perkembangan kehidupan berdemokrasi di negara ini nampak menuju titik kurva yang merendah, bahkan mungkin semakin turun ke garis terbawah dalam sejarah kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.
Walaupun seperti itu, semestinya masyarakat kita mulai menempati kondisi kehidupan berdemokrasi yang lebih terbuka, egaliter, dan berorientasi kepada kompetensi, keberpihakan kepada semangat reformasi dalam menjalankan atau mempraktikkan sistem demokrasi yang tonggaknya dimulai pasca keruntuhan rezim otoriter tahun 1998.
Mahkamah menjadwalkan pembacaan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan pemohon Dedek Prayudi dengan kuasa hukum Michael pada pukul 10.00 WIB.
Sebagaimana kita maklumi, putusan MK nanti, akan membawa pengaruh pada kontestasi Pilpres 2024. Peluang Gibran Rakabuming Raka ditentukan lewat putusan MK tersebut, dan akan menjadi angin segar bagi capres yang sudah membidiknya jika MK memutuskan batas usia minimal capres cawapres di angka usia 35 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.
Nama Gibran kerap disebut sebagai salah satu kandidat potensial cawapres dari Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Meski partai Gerindra telah didukung oleh Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora dan Partai Garuda, nampaknya popularitas Gibran sangat menggoda.
Apa yang beberapa waktu lalu disebut Presiden Jokowi sedang ‘cawe-cawe’, kini indikator yang jelas menujukkan aksi itu benar adanya menurut saya. Dorongan Jokowi untuk merestui Kaesang menjadi ketua umum PSI, dan adanya upaya menggugat Undang-Undang batas usia pencalonan capres cawapres jadi bukti bahwa Jokowi bukan sekedar ‘cawe-cawe’ atas nama agar kontestasi piplres 2024 berjalan seusai Undang-Undang Pemilu, tapi ada “pesan” tersirat, bahwa ia ingin meneruskan kekuasaannya lewat dinasti keluarga.
Tentu dinasti dalam sistem demokrasi bukan sesuatu yang menyalahi Undang-Undang. Hak setiap warga negara mendapat jaminan untuk berkarir dan berkiprah di dunia politik, sebagai apapun.
Popularitas politik v.s. kompetensi leadership
73 tahun Indonesia merdeka bagi saya adalah waktu yang tidak sedikit. Jika kita ibaratkan itu usia seseorang, maka kualitas kedewasaannya, kemampuan berpikirnya, kebijaksanaannya hingga pandangannya tentang kehidupan akan sangat matang.
Negara ini idealnya sudah sedemikian maju, kaya, besar dan berpengaruh, karena dari berbagai aspek yang menjadi modalitas hal-hal tersebut ada dan tersedia.
Namun sayangnya kompetensi leadership para pemimpin yang pernah ada tidak menyisakan sejarah kehidupan berdemokrasi yang baik, melahirkan sistem kehidupan yang sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Realitasnya, tidak menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
Setelah keruntuhan rezim Orde Baru, semangat demokrasi bangsa ini demikian tinggi. berbagai upaya dan evaluasi dilakukan untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang besar, yang berdaulat dan memiliki nilai-nilai tinggi pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu, otoritaniasime dalam kekuasaan adalah pengalaman buruk yang harus dihapus dan ditinggalkan. Maka konsekwensilogisnya partisipasi sosial politik harus dibangun dengan dasar yang kuat, memiliki kualitas kompetensi yang baik, dan tentu harus bertolak belakang dengan pola yang dilakukan oleh penguasa sebelum era reformasi.
Gambaran harapan itu menurut saya semakin kabur dan luntur. garis-garis yang menghubungkan, titik-titik yang disatukan dalam rajut tali kehidupan berbangsa yang adil, demokratis dan menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, tercampur dan juga tertutup debu atau noda runtuhnya prinsip keadilan dan tumbuhnya kembali kultur-kultur lama yang harusnya ditinggalkan.
Kini popularitas jauh meninggalkan kapasitas dan kompetensi leadership dalam kancah persaingan tampuk kepemimpinan bangsa atau kepemimpinan politik.
Salah satu akar permasalahan dari jebakan para capres yang akan berkontestasi tahun depan adalah ambang batas 20 % (presidential treshold) sebagai syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Ini memang jadi semacam “jebakan” bagi demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa yang memiliki kompetensi karena karirnya di dunia politik dan integritasnya dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur dan visi misinya untuk memajukan bangsa.
Kemudian jebakan itu mengunci kader-kader partai yang berkualitas dengan sistem yang dibuat untuk memuluskan personal yang dianggap populer dari kalangan tertentu lewat partai yang sudah mengantongi ambang batas minimal tersebut.
Kemudian mendiskualifikasi calon-calon pemimpin – bilamana tidak didukung oleh partai atau koalisi partai jika tidak memenuhi elektabilitas yang disunting dari populatitas.
Oleh karena itu, tidak perlu dipandang sesuatu yang ‘absurd’ jika orang seperti Kesang ‘ujug-ujug’ jadi ketua umum partai tanpa pemikiran dan gagasan cemerlang sebagai pemimpin organisasi politik.
Jadi, tidaklah heran jika sosok seperti Prabowo yang memiliki pengalaman luar biasa di kancah politik serta memiliki “modal” untuk menciptakan miliu pengkaderan pemimpin bangsa harus tergoda oleh sosok Gibran karena popularitasnya, atau karena ia ditakdirkan lahir sebagai calon penerus dinasti kekuasaan.